Le Tibalique
Suatu hari aku melihat para penduduk desa menggali kuburan
seorang laki-laki tua. Setelah itu mereka baringkan ia di kediamannya. Lelaki tua
itu kejang-kejang hingga berangsur-angsur menjadi tenang. Perlahan ia membuka
matanya. Di sampingnya adalah wanita yang kurasa adalah istrinya. Ia bilang,
selamat datang, Sayang.
Seiring dengan berjalannya waktu, jadilah kutahu lelaki itu
bernama Jamai. Di depan mataku semuanya terjadi, bahwa Jamai yang tua semakin
hari semakin muda. Keriputnya hilang dimakan waktu, hingga ia dapat pergi kerja
dan memulai aktivitas kerjanya. Pada hari pertamanya bekerja, semua orang berbisik-bisik, bahwa bos besar telah datang.
Suatu
hari, sepulang kerja, ia kabarkan pada istrinya yang bernama Ika, “aku akan
pergi menggali kubur ibuku.” Sambil terus membolak-balik makanan di atas
penggorengan, Ika bertanya kapan Jamai akan pulang. Jamai bilang sebelum gelap
ia akan sudah ada di rumah.
Maka Jamai pergi dengan beberapa pemuda desa lainnya, menggali kubur ibunya. Ibu Jamai
nampak pucat di liang lahat. Kedua matanya terpejam rapat. Jamai segera membawanya ke
rumah sakit. Di sana, ia menangis, berulang kali mengucap ia rindu. Jamai belum
pernah bertemu ibunya, tapi ia merasakan sebuah rindu. Tak hanya rindu, ada sebuah perasaan yang begitu besar yang ia rasakan untuk wanita itu. Perasaan apa itu? Ia sendiri tak yakin harus menyebutnya dengan
sebutan apa. Kasih sayang-kah? Ah, rasanya lebih dari sekedar kasih sayang. Kepada ibunya lah
Jamai akan kembali, sejauh apapun ia pergi.
“Ibu, akhirnya bangun,” Jamai mengecup kening ibunya yang
berkerut-kerut. “Selamat datang,” ujar Jamai.
Ibu Jamai memeluk Jamai dan menitikkan air matanya. “Ayahmu
pasti akan begitu senang melihatmu”
“Dua bulan dari sekarang, Bu, kita akan bertemu ayah," Jamai mengelus-elus punggung tangan ibunya.
Dan, itulah yang terjadi. Dua bulan setelah pertemuan pertama Jamai dan ibunya, ayah Jamai datang ke kehidupan, membuat hidup ibu Jamai maupun Jamai terasa lengkap. Ika pun bahagia menyambut kedatangan ayah Jamai yang baginya sudah seperti ayah sendiri.
Pada suatu hari, ketika hampir tak ada sehelai lagipun rambut putih
di kepala kedua orangtua Jamai, diadakanlah sebuah perayaan pernikahan untuk
Jamai dan Ika. Disana, Ika maupun Jamai menangis tersedu-sedu. Kini sudah
saatnya mereka untuk menjalani fase hidup selanjutnya. Ika berkata, ia sungguh
begitu bahagia untuk kembali ke kampung halamannya dan tinggal bersama kedua
orangtua kandungnya, tapi ia juga sekaligus sedih untuk meninggalkan
Jamai, yang dengannya ia telah habiskan hampir separuh hidupnya.
Jamai dan Ika pun pada akhirnya hidup masing-masing, tumbuh
menjadi dua manusia muda yang hampir tak lagi bisa mengingat satu sama lain.
Jamai perlahan lupa bahwa ada separuh jiwanya yang bernama Ika, begitupun Ika
yang kadang lupa bahwa ada separuh jiwanya yang bernama Jamai.
Hari-hari Jamai berlalu seperti biasa. Jamai dan semua orang
lain masih terus tumbuh muda dan mengecil, daun-daun kembali ke rantingnya, dan musim dingin
berganti menjadi musim gugur yang berganti menjadi musim panas yang berganti
menjadi musim semi. Ilmu-ilmu yang mereka miliki perlahan terlepas, rontok dari
kepala – setiap manusia pada akhirnya masuk juga ke masa kanak-kanak.
Hingga pada akhirnya, suatu hari Jamai terbangun di musim
panas yang terik, menemukan kakinya yang tak mampu lagi berjalan. Bukannya membaik,
semakin hari telapak kakinya malah semakin tumpul, membuatnya hanya bisa
berbaring di kasur, atau di pangkuan ibunya.
Jamai kini tak dapat memberikan presentasi tentang naik
turunnya keadaan ekonomi di negaranya, atau menulis sebuah proposal penting
yang tebalnya beratus-ratus halaman. Mengucap sepatah katapun ia tak mampu. Pada
akhirnya yang keluar hanyalah racauan dan gumaman. Jamai menangis jika merasa
gagal mengungkapkan apa yang ia ingin ungkapkan, dan ini terjadi tak hanya
sekali.
20 November 1970 adalah hari yang tak akan pernah dilupakan
kedua orangtua Jamai. Jamai sedang diayun dengan satu tangan ibunya waktu
ibunya menyadari wajah Jamai yang perlahan memerah, dan kulitnya terasa
menipis. Ibu Jamai segera menelepon suaminya di
tempat kerja, dengan nada sedikit panik ia kabarkan, “sudah waktunya!”
Ayah Jamai mengebut mobilnya, kembali ke rumah. Ibu Jamai
sudah menunggu di depan rumah dengan tas tangannya di tangan kiri, dan Jamai di
tangan kanan. Hari itu pula mereka pergi ke rumah sakit terdekat dan ibu Jamai
mengelus anaknya sepanjang perjalanan di mobil. Ayah Jamai pun sesekali mencuri
pandang, melihat anaknya yang tertidur nyaman. “Perhatikan jalan!” Ibu Jamai
harus beberapa kali mengingatkan. “Anakku terlalu tampan!” Balas suaminya.
Sampai di rumah sakit, dengan kursi roda, ibu Jamai dibawa
ke ruang bersalin.
Jamai menangis begitu lama di ruang bersalin tersebut,
hingga akhirnya mulutnya terbungkam, matanya terpejam, ia dibuai oleh rasa
nyaman yang melenakan. Dari seluruh tempat yang pernah ia kunjungi, rasanya ini adalah tempat paling nyaman yang pernah ia singgahi. Dulu sekali, Jamai ingat, ia pernah mempelajari soal tempat ini di sekolah. Kalau tidak salah, Rahim namanya.

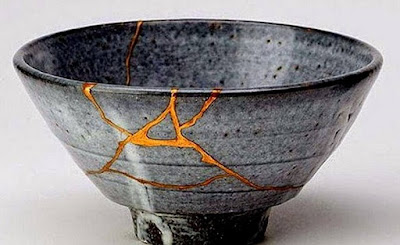
Comments
Post a Comment